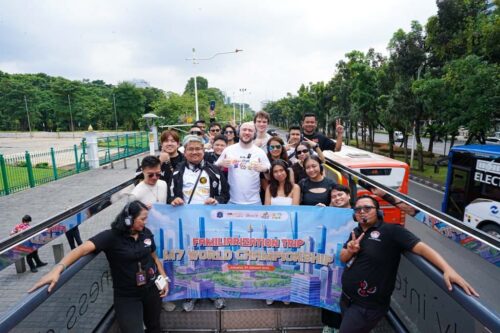NEOLIBERALISME ITU ANTI SUBSIDI

Oleh: Yudhie Haryono (CEO Nusantara Centre) & Agus Rizal (Ekonom Universitas MH Thamrin)
Jika subsidi dihapus, yang terjadi pasar makin rakus. Inilah temuan dari praktik neoliberalisme (rezim pasar bebas) yang “mengharamkan subsidi.” Ya. Doktrin itu sudah lama. Negeri kita ikut tanpa kritis. Membebek bak makhluk tanpa nalar dan kecerdasan. Ya, neoliberalisme memang secara fundamental memusuhi subsidi karena dianggap mengganggu “kemurnian” mekanisme pasar.
Bagi aliran ini, harga harus bergerak mengikuti kompetisi tanpa campur tangan negara. Begitu negara turun tangan melalui subsidi, pasar dinilai “tidak efisien.” Klaim ini terdengar rasional, padahal hanya doktrin ideologis yang menyingkirkan realitas sosial: pasar diutamakan, warga dikorbankan. Orang kaya disubsidi dan diproteksi, orang miskin dipajaki dan dibiarkan mati.
Logika neoliberal bertumpu pada keyakinan bahwa pasar selalu bisa mengatur dirinya sendiri. Ketika harga pangan, energi, kesehatan, pendidikan atau transportasi dinaikkan dengan alasan subsidi membebani anggaran, neoliberalisme menganggapnya langkah sehat. Padahal, pasar bukan ruang netral. Ia dikendalikan pemain bermodal besar yang sejak awal jauh lebih kuat dibanding warga biasa dan pelaku usaha kecil. Tanpa subsidi, warga langsung berhadapan dengan kekuatan pasar yang timpang, bukan dengan persaingan yang adil.
Neoliberalisme mengklaim ingin pemerintah lepas tangan dari ekonomi, tetapi realitasnya pencabutan subsidi justru menyiapkan panggung dominasi baru: intervensi korporasi. Perusahaan raksasa bebas menentukan harga, menguasai distribusi, bahkan memonopoli kebutuhan dasar. Negara mundur, tetapi korporasi maju mengambil alih. Penolakan subsidi bukan perjuangan efisiensi, melainkan strategi menyerahkan pasar publik kepada privat tanpa kontrol.
Subsidi dibenci neoliberalisme karena memperkuat peran negara dalam mengatur distribusi kesejahteraan. Negara yang aktif dianggap menghambat ekspansi swasta. Bila negara tetap membiayai pendidikan, kesehatan, energi, atau pangan, ruang profit swasta menyempit. Di sinilah masalah bagi neoliberalisme: subsidi dianggap bukan hanya beban fiskal, tetapi hambatan politik terhadap akumulasi keuntungan korporasi.
Ironi neoliberalisme adalah klaim bahwa pasar bebas menciptakan kompetisi adil. Faktanya, tanpa subsidi pelaku kecil ditinggalkan tanpa pelindung dalam persaingan yang jelas tidak setara. Subsidi sektor vital tidak mematikan persaingan, justru menciptakan peluang bagi usaha kecil tetap hidup. Tanpa subsidi, persaingan berubah menjadi seleksi alam brutal: yang kuat menguasai segalanya, yang lemah tersingkir bahkan sebelum mulai bertanding.
Neoliberalisme juga menyesatkan publik dengan menuding subsidi sebagai “beban APBN.” Nyatanya, subsidi adalah hak warga untuk mengakses layanan dasar. Pengurangan subsidi pun tidak dialihkan untuk pelayanan publik, tetapi lebih sering diberikan pada insentif investasi, tax holiday, atau jaminan infrastruktur untuk perusahaan besar. Warga diminta berhemat, sementara korporasi dimanjakan dengan fasilitas negara.
Jika negara terus memberikan subsidi, maka harga tidak tunduk pada “standar pasar” versi neoliberalisme dan sulit dikuasai kepentingan privat. Subsidi menjaga agar harga barang publik tunduk pada kepentingan warga, bukan pada kalkulasi laba. Itulah ancaman terbesar bagi neoliberalisme: pasar yang dilindungi negara tidak mudah dimasuki, tidak gampang diprivatisasi, dan tidak bisa dimainkan sebagai ladang rente.
Pada akhirnya, neoliberalisme bukan pelepasan pasar dari kontrol, tetapi pemindahan kontrol dari publik ke kantong privat. Ketika subsidi dicabut, sektor publik kehilangan pelindung dan langsung menjadi arena spekulasi harga. Para spekulan akan melahirkan mafia, para mafia akan melahirkan konglomerasi, para konglomerasi akan melahirkan oligarki. Empat actor inilah yang nanti mengganti negara dalam skala ekonomi nasional.
Nah, yang terjadi sesungguhnya kontrol bergeser, bukan menghilang: dari negara yang mewakili warganya, ke segelintir pemilik modal yang menjadikan kebutuhan dasar sebagai komoditas untuk dimanipulasi. Singkatnya, subsidi bukan beban fiskal; ia adalah benteng terakhir agar ekonomi tidak berubah menjadi mesin pemeras warganya sendiri; pemaria dan pemangsa semua manusia yang lemah.
Singkatnya, kita butuh praktik subsidi karena kegiatan ini dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan efisiensi ekonomi. Praktik ini akan meningkatkan aksesibilitas; mengurangi kemiskinan, kesakitan, pengangguran; meningkatkan efisiensi ekonomi; meningkatkan investasi; meningkatkan kesejahteraan warga-negara.
Jika pasar bebas anti subsidi, tentu saja karena mereka tidak punya konstitusi, tidak punya pancasila; moralnya akumulasi kapital, bukan akumulasi kaya bersama. Targetnya kaya dirinya, keluarganya, kelompoknya saja. Tentu saja, ia pasti anti konstitusi, anti sosial, anti kemanusiaan, dan anti cita-cita para pendiri republik Indonesia.
Ingat, Bung Hatta (1902-1980) sering berfatwa, “selama masih banyak kebodohan, pengangguran dan kemiskinan maka negara wajib jadi panitia kesejahteraan dan kesentosaan warganya.” Tugas panitia itu jelas: memastikan warganya sejahtera apapun caranya termasuk dengan subsidi (silang) dan proteksi. Tanpa itu, arsitektur ekonomi kita tetap kolonial dan menindas. Dus, praktik subsidi sebenarnya bagian dari revolusi ekonomi secara fungsional, struktural dan subtansial. Dan, semua itu selaras dengan cita-cita republik seperti dalam pembukaan konstitusi. Semoga.(*)