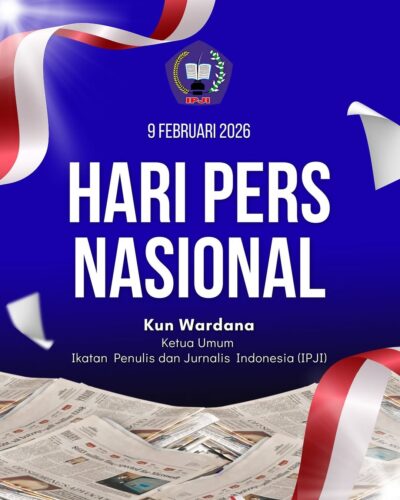Mengembalikan Ekonomi ke Tangan Warga Negara

Oleh: Yudhie Haryono (Presidium Forum Negarawan) & Agus Rizal (Ekonom Univ. MH Thamrin)
Otoritas.co.id – Jenderal Soedirman pernah berpesan (1945): “Kebebasan, termasuk kebebasan ekonomi, berarti bebas melakukan semua kebaikan, bukan bebas berbuat kejahatan tanpa dapat diadili. Ekonomi akan sehat bila dikerjakan oleh semua, untuk semua, dan demi kebaikan bersama.”
Pesan ini menegaskan bahwa subjek ekonomi seharusnya adalah seluruh warga negara, bukan segelintir individu, kelompok, oligarki, apalagi asing.
Sejarah bangsa pun menunjukkan hal serupa. Bung Karno (1944) menekankan bahwa kemerdekaan tidak cukup hanya membebaskan diri dari penjajahan politik, melainkan juga dari belenggu ekonomi. Bung Hatta (1946) melengkapinya: politik hanyalah pintu gerbang, sedangkan kemerdekaan sejati baru lahir bila ekonomi rakyat berdiri di atas sokoguru koperasi, gotong royong, dan kemandirian.
Namun perjalanan pembangunan kerap melenceng dari cita-cita itu. Pasal 33 UUD 1945 jelas memerintahkan bumi, air, dan cabang produksi penting dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat. Sayangnya, tafsir yang sempit menjadikan negara hanya sebagai regulator, sehingga aset vital jatuh ke tangan korporasi besar, bahkan asing. Akibatnya, kontrol atas kekayaan bangsa perlahan lepas dari genggaman rakyat sendiri.
Negara yang kehilangan aset strategis sama saja kehilangan kepentingan nasional. Tanpa kepentingan nasional, tidak ada lembaga penjaga, tidak ada legislasi yang berpihak, dan negara berpotensi berubah menjadi milik swasta atau bahkan mafia. Warga pun hanya menjadi penonton, paria di negeri sendiri.
Di sinilah pentingnya kehadiran Undang-Undang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial. Undang-undang ini bukan hanya mandat konstitusi, tetapi kebutuhan strategis. Ia harus memastikan penguasaan aset nasional, distribusi sumber daya yang adil, penguatan koperasi dan BUMN, serta mencegah praktik masa lalu yang merugikan rakyat—seperti rekapitalisasi perbankan 1998, ketika kerugian swasta justru ditanggung publik.
Logika ini sejalan dengan teori developmental state dan konsep embedded autonomy (Peter B. Evans, 1989): negara yang kuat, otonom, dan terhubung dengan rakyat mampu memimpin industrialisasi sekaligus mendistribusikan manfaatnya secara adil.
Sayangnya, sebagian ekonom justru menjadi corong kepentingan modal, membungkus liberalisasi dengan jargon “efisiensi.” Akhirnya, negara diprivatisasi, rakyat dipariakan. Padahal, Pancasila dan UUD 1945 sudah menyediakan panduan jelas: ekonomi berbasis kekeluargaan, gotong royong, dan keberpihakan pada rakyat.
Realitas hari ini membuktikan urgensinya. Harga pangan mudah goyah akibat impor, lahan produktif menyusut, UMKM kesulitan akses modal, generasi muda kehilangan harapan di sektor riil. Ketergantungan pada impor dan modal asing membuat Indonesia terjebak dalam pola dependency: sekadar pemasok bahan mentah, pasar konsumsi, dan tenaga murah.
Karena itu, mengembalikan ekonomi ke tangan rakyat melalui UU Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial adalah langkah konstitusional sekaligus keberanian politik. Dengan sistem baru, kekuasaan ekonomi bisa digeser dari segelintir pemodal ke mayoritas warga. Jika konsisten ditempuh, cita-cita Indonesia Emas 2045 bukan sekadar mimpi, melainkan kenyataan yang hadir lebih cepat.
Tan Malaka (1943) pernah mengingatkan: “Karena tindakan ekonomilah kelak yang akan menentukan kemakmuran rakyat dan keamanan republik kita. Rencana ekonomi negara yang berdaulatlah kuncinya.”
Kini, pilihan ada di tangan kita: tetap menjadi pasar bagi bangsa lain, atau berdiri tegak sebagai bangsa berdaulat penuh atas ekonominya sendiri.