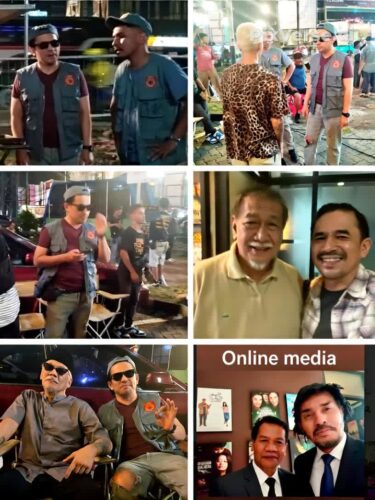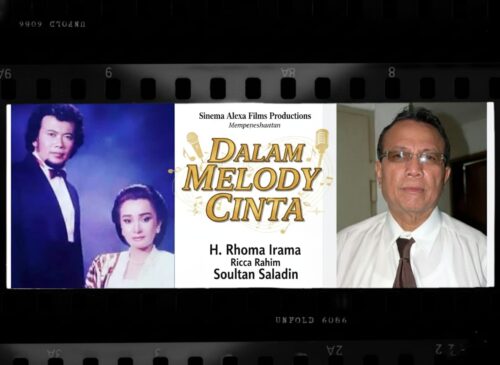KEHARUSAN HILIRISASI ENERGI HIJAU
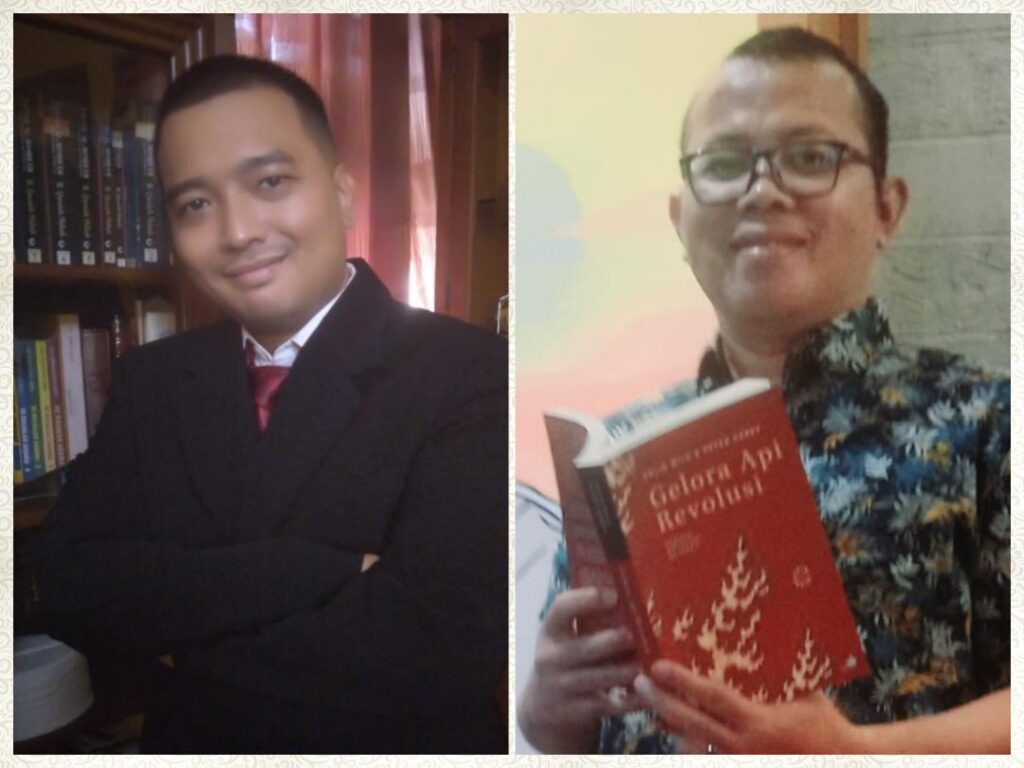
Oleh: Yudhie Haryono (Presidium Forum Negarawan) dan Agus Rizal (Ekonom Univ MH Thamrin)
Mau menguasai pasar dunia? Reindustrialisasi dan hilirisasi adalah jawabannya. Maka, kedua program tersebut memasuki tahap yang tidak bisa lagi ditunda. Keduanya keniscayaan, tak bisa dielakkan. Ketergantungan panjang pada ekspor komoditas mentah hanya makin melemahkan daya saing nasional, menciptakan mafia impor-ekspor dan melemahkan ekonomi warga miskin.
Atas alasan di atas, RUU Perekonomian Nasional mendorong transformasi menuju industri berbasis nilai tambah dan energi hijau. Namun transformasi ini tersendat karena fondasi energi yang belum siap. Negara ingin melompat ke fase industri modern, tetapi infrastruktur energinya tertinggal jauh di belakang.
Di titik inilah hilirisasi muncul sebagai strategi penting untuk memperkuat struktur industri. Hilirisasi dimaksudkan untuk mengolah kekayaan alam di dalam negeri dan memindahkan pusat keuntungan nasional dari ekspor bahan mentah ke ekspor produk bernilai tambah.
Namun, proses pengolahan tersebut membutuhkan energi stabil, murah, dan bersih. Tanpa energi yang memadai, hilirisasi kehilangan fungsi penguatnya dan justru menambah biaya produksi. Ini menunjukkan bahwa industrialisasi dan hilirisasi tidak bisa berjalan jika agenda energi bersih tertinggal. Ini program yang saling berkelindan. Koordinasi dan peta jalan subtantif menjadi tidak tak terelakan.
Ketertinggalan energi ini semakin kentara karena sebagian besar industri masih mengandalkan energi fosil yang mahal dan tidak konsisten. Transisi energi yang digagas pemerintah belum berjalan secepat ekspansi kawasan industri. Di banyak daerah, kebijakan energi dan kebijakan hilirisasi tidak pernah duduk dalam satu rencana. Akibatnya, industri menghadapi biaya tinggi, ketidakpastian suplai, dan risiko investasi yang meningkat.
Hilirisasi yang seharusnya memperkuat ekonomi nasional justru melambat karena tidak didukung oleh sumber energi yang layak. Akar masalahnya lebih dalam: Indonesia selama puluhan tahun mengikuti pola neoliberalisme yang mendorong ekspor mentah dan ketergantungan pada energi fosil murah. Pola ini menempatkan negara dalam posisi pinggiran rantai produksi global.
Karena itu, peralihan ke energi bersih bukan hanya tuntutan lingkungan, tetapi upaya keluar dari struktur ekonomi lama yang menghambat industrialisasi. Energi bersih adalah prasyarat untuk membangun industri yang efisien, berkelanjutan, dan tidak lagi dikendalikan oleh logika ekonomi kolonial berbasis ekstraksi.
RUU Perekonomian Nasional yang digagas oleh para ekonom pancasilais sebenarnya sudah memberikan jalur untuk memperluas energi terbarukan dan menata konektivitas energi lintas wilayah. Namun implementasinya belum sinkron dengan kebutuhan industri di lapangan. Daerah belum menyiapkan peta kebutuhan energi bersih yang selaras dengan rencana hilirisasi sektor mineral, pangan, atau manufaktur strategis. Akibatnya, percepatan industri berdiri di atas fondasi yang rapuh: ada pabrik, tetapi tidak ada energi yang mampu menggerakkannya secara konsisten.
Dampak langsungnya terlihat pada biaya produksi yang terus naik. Pelaku industri terpaksa menahan ekspansi, mengurangi kapasitas, atau menunda investasi baru karena pasokan energi tidak dapat diandalkan. Negara mendorong peningkatan nilai tambah, tetapi tidak menyediakan kondisi dasar yang membuat nilai tambah itu mungkin terjadi.
Ketidakpastian ini membuat hilirisasi sulit berfungsi sebagai motor pertumbuhan, karena proses industrialisasi berdiri di atas sistem energi yang tidak stabil. Tentu saja ini pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan. Mudah dikatakan, tak mudah diimplementasikan.
Untuk memperbaiki situasi ini, negara membutuhkan peta jalan energi bersih yang terintegrasi penuh dengan arah industrialisasi nasional. Peta itu harus disertai standar energi untuk setiap kawasan industri strategis, penguatan jaringan transmisi, dan percepatan pembangkit energi terbarukan.
Penyediaan energi bersih bukan isu teknis, tetapi keputusan politik yang menentukan apakah industrialisasi Indonesia benar-benar akan berjalan atau hanya menjadi wacana jangka panjang. Penyediaan ini menjadi titik tumpu bagi pergerakan reindustrialisasi dan hilirisasi menuju titik tuju: menguasai pasar internasional; memenangkan perang dagang; memartabatkan warga-negara.
Selama ini, arah kebijakan ekonomi Indonesia juga dipengaruhi oleh keyakinan pada teori “destruksi kreatif” ala Schumpeter (1883-1950) yang menyebut industri kita tanpa perlindungan legislatif yang adil. Ya, hal ini karena mazhab neoliberalisme mengajarkan bahwa pelaku kecil yang kalah harus tersingkir demi efisiensi.
Pada akhirnya, industri kecil dan koperasi menjadi korban dan tumbal: mereka kalah oleh modal besar, regulasi yang berat sebelah, serta minimnya dukungan energi dan teknologi. Tentu, ini melemahkan fondasi ekonomi nasional karena pelaku kecil dan menengah adalah inti dari ketahanan industri.
Pandangan Daron Acemoglu, peraih Nobel Ekonomi 2024, memberikan peringatan keras terhadap pola tersebut. Bersama James Robinson, ia menunjukkan bahwa kemakmuran hanya tumbuh dari inclusive institutions—lembaga yang memberi akses, ruang partisipasi, dan peluang inovasi bagi banyak pihak. Kita menyebutnya “gotong-royong” dan kolaboratif.
Sebaliknya, pola extractive institutions menutup akses dan menguntungkan segelintir pelaku besar. Di Indonesia, neoliberalisme bukan sekadar ide ekonomi, tetapi proyek institusi yang memperkuat struktur eksklusif: negara bekerja untuk modal besar, bukan untuk ekosistem industri secara keseluruhan.
Singkatnya, tanpa institusi yang inklusif dan negara yang progresif, industrialisasi, hilirisasi, dan energi hijau hanya akan menjadi agenda indah yang gagal menembus realitas. Tentu saja, kita semua tidak ingin itu terjadi.(*)