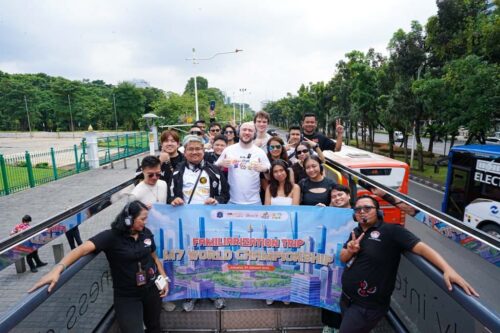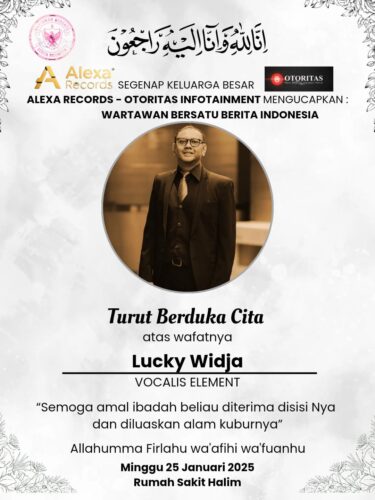EKONOMI PANCASILA MENGATASI PENGANGGURAN
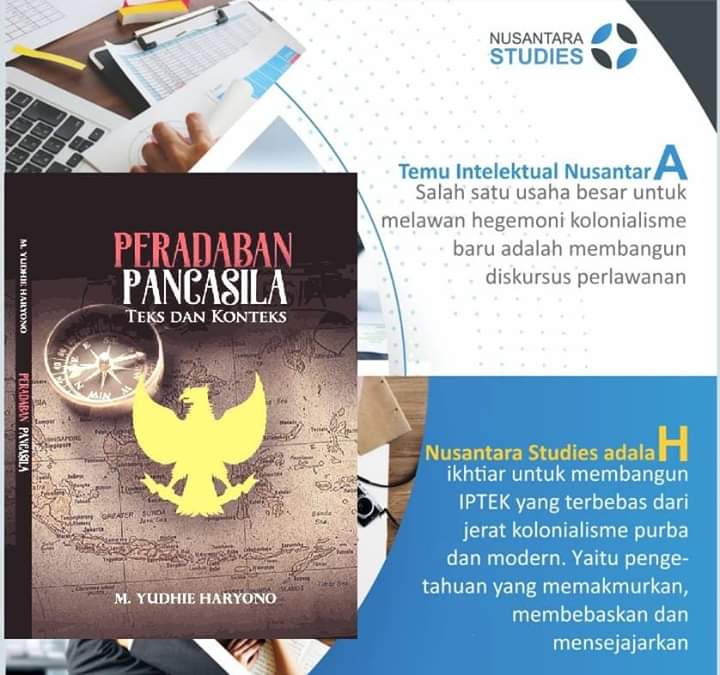
Oleh: Yudhie Haryono (Presidium Forum Negarawan) & Agus Rizal (Ekonom Univ MH Thamrin)
Otoritas.co.id — Dengan realisasi investasi sebesar Rp 1.714,2 triliun pada akhir tahun 2024, mengapa pengangguran tak bisa dihabisi? Pasti karena salah sistem ekonominya, yang diperparah oleh tindakan agensinya. Bagaimana kisahnya?
Per bulan Februari 2025, jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 7,28 juta orang. Angka ini meningkat 83 ribu dibanding tahun sebelumnya. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) secara persentase memang turun tipis menjadi 4,76 persen, tapi ini bukan pertanda membaiknya kualitas penyerapan kerja.
Banyak warga yang keluar dari hitungan angkatan kerja karena frustrasi, menyerah mencari kerja, atau terjebak dalam pekerjaan informal tanpa perlindungan. Ini menunjukkan bahwa sistem ekonomi kita belum mampu menjalankan fungsinya secara adil dan menyeluruh bagi seluruh warga negara.
Kelompok usia muda menjadi yang paling terpukul. TPT untuk usia 15–24 tahun mencapai 16,16 persen, jauh di atas rerata nasional. Sementara kelompok usia di atas 25 tahun justru lebih stabil. Ini menandakan gagalnya sistem untuk membuka pintu produktivitas bagi generasi baru. Mereka bukan hanya tidak bekerja, tetapi juga kehilangan prospek, karena yang tersedia lebih banyak pekerjaan bersifat sementara, padat tekanan, dan minim kepastian hukum. Ketimpangan antar kelompok usia ini mengindikasikan sistem yang tidak berkelanjutan.
Selama tiga dekade terakhir, arah pembangunan ekonomi nasional lebih condong pada kerangka neoliberal yang menempatkan pertumbuhan sebagai tujuan utama, bukan alat. Liberalisasi sektor tenaga kerja, penekanan terhadap efisiensi, dan ketergantungan pada modal asing menciptakan struktur ekonomi yang timpang. Negara makin kehilangan peran strategisnya dalam penciptaan kerja dan perlindungan produktivitas warganya. Di bawah pendekatan ini, kerja direduksi menjadi komoditas, sementara manusia diposisikan hanya sebagai roda dalam mesin kapital.
Pengangguran tidak bisa diselesaikan hanya dengan pelatihan kerja, promosi wirausaha, atau deregulasi pasar tenaga kerja. Masalahnya bukan sekadar keterampilan atau mismatch, tetapi soal kendali atas alat produksi dan arah pembangunan nasional. Ketika warga negara tidak memiliki kuasa atas tanah, alat, atau struktur pendukung, maka tak akan lahir kedaulatan ekonomi. Tanpa kedaulatan, kerja hanya menjadi sarana bertahan hidup, bukan jalan menuju martabat.
Dalam kerangka ini, ekonomi Pancasila seharusnya bukan sekadar jargon atau hiasan perundang-undangan, melainkan fondasi utama yang mengarahkan seluruh kebijakan ekonomi. Pancasila bukan hanya dasar negara, melainkan jati diri warga negara. Nilai-nilai keadilan sosial, kemanusiaan yang adil dan beradab, serta musyawarah dalam pengambilan keputusan ekonomi harus diaktualkan secara konkret dalam kebijakan anggaran, pembangunan, dan tenaga kerja. Tidak cukup hanya menyebut “ekonomi Pancasila” jika praktiknya masih tunduk pada logika pasar bebas yang menyingkirkan si lemah, si cacat dan si bodoh.
Peran koperasi dalam sistem ekonomi Pancasila semestinya ditempatkan sebagai alat demokratisasi kepemilikan dan produksi. Tapi selama koperasi hanya dianggap pelengkap dari sistem kapitalisme, bukan sebagai bentuk utama kelembagaan ekonomi warga-negara, maka dampaknya akan tetap terbatas. Koperasi harus menjadi tempat warga negara mengelola hasil produksinya secara bersama, saling melindungi dari risiko pasar, dan membangun kemandirian ekonomi berbasis komunitas.
Di sektor desa, pertanian dan kelautan, negara harus kembali menjadi penjaga keberlanjutan, bukan hanya fasilitator investasi. Akses terhadap tanah, air, dan pasar harus dikembalikan kepada warga negara sebagai hak, bukan sebagai imbalan. Pertanian rakyat, industri rumah tangga, dan kerajinan berbasis lokal jauh lebih menyerap tenaga kerja dan menciptakan ketahanan ekonomi dibanding industri berskala besar yang padat modal tapi minim tenaga kerja. Logika inilah yang perlu ditegakkan kembali oleh negara.
Sektor pendidikan pun perlu diorientasikan ulang. Tujuan pendidikan bukan sekadar menyiapkan buruh yang siap diserap pasar, tapi menumbuhkan manusia merdeka yang mampu menciptakan kerja, bukan sekadar mencari kerja. Pendidikan yang berpihak pada ekonomi Pancasila akan mendorong integrasi antara pengetahuan, keterampilan, dan keberpihakan sosial. Bukan hanya kompeten secara teknis, tapi juga sadar peran dalam pembangunan nasional yang adil.
Pengangguran adalah gejala dari kegagalan sistem yang telah terlalu lama mengabaikan arah pembangunan yang berkeadilan. Jika ekonomi terus digerakkan oleh kepentingan akumulasi dan bukan keberlanjutan sosial, maka pengangguran dan ketimpangan hanya akan menjadi konsekuensi permanen. Kita tidak kekurangan tenaga kerja, kita kekurangan sistem yang berpihak.
Sudah saatnya kita berhenti menambal sistem yang salah arah. Pancasila bukan sekadar simbol, tapi harus menjadi perangkat hidup ekonomi nasional. Mengatasi pengangguran bukan hanya soal membuka lapangan kerja, tetapi mengembalikan martabat warga negara sebagai pemilik, pelaku, dan penentu arah ekonomi bangsanya sendiri.(*)