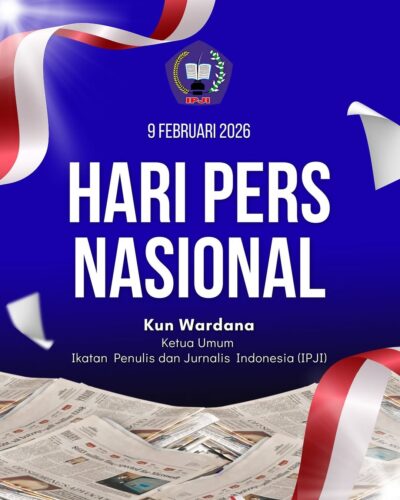ARUS BALIK NUSANTARAISME

Oleh: Yudhie Haryono, Rektor Universitas Nusantara
Otoritas.co.id – Pelan namun pasti, gelombang baru diskursus nusantaraisme mulai tumbuh. Ia hadir sebagai antitesis terhadap gerakan anti-intelektualisme yang kini justru disokong dan dipraktikkan oleh sebagian elite politik. Bila poros anti-intelektualisme berpusat di istana, maka arus balik nusantaraisme berdenyut di kerajaan-kerajaan pikiran, di lingkar para bangsawan nalar. Jika anti-intelektualisme memuja proyek membangun raga, nusantaraisme memilih membangun jiwa.
Konteks ini seperti pertarungan antara masa jahiliyah dan kejernihan nalar. Sebab, inti arus balik nusantaraisme terletak pada kebijaksanaan lokal, kearifan tradisi, dan local genius. Ia bukan sekadar nostalgia, melainkan sebuah post-tradisionalisme—meneguhkan kejernihan tradisi lama untuk menjawab problem zaman yang gagal dipecahkan oleh logika dan produk modernisme.
Kearifan lokal menjadi pandangan hidup, dasar ilmu pengetahuan, sekaligus strategi kehidupan. Di sini, masyarakat yang waras, bernalar, dan berhati mulia menjadikannya pedoman untuk memenuhi kebutuhan kebangsaan dan kenegaraan. Inilah yang membedakan nusantaraisme dari anti-intelektualisme.
Kita tahu, mazhab anti-intelektualisme bergerak stabil dengan ciri anti-moralitas, anti-nalar, dan anti-historitas. Amoralisme adalah penyakit yang melanggar hukum moral, norma, dan standar kemanusiaan. Ia lahir dari perilaku warga—dan elite—yang tahu suatu hal salah, namun tetap melakukannya.
Penyakit ini menular cepat, membentuk masyarakat yang kehilangan konsensus kemanusiaan, membisukan akal budi, dan mengabaikan kesetiaan sejarah. Pemerintahan pun kehilangan kejeniusannya karena kompetensi dan kesiapan kerjanya rendah—akibat proses pemahaman ipoleksosbudhankam yang dangkal.
Dalam banyak kajian, amoralisme tumbuh dari kurikulum feodal, tradisi dendam, dan laku fasis. Ia anti-sains karena membuang nalar ke selokan. Di dalamnya, tidak ada perhatian pada metode riset ilmiah maupun filsafat sains—baik ontologi (hakikat objek ilmu), epistemologi (cara mendapatkan pengetahuan yang benar), maupun aksiologi (nilai dan manfaat pengetahuan).
Sebaliknya, arus balik nusantaraisme menjadikan moral sebagai tulang punggung kehidupan. Ia adalah buah dari nalar kosmopolit yang jenius. Ada lima pilar yang menjadi penopangnya:
- Pembentukan ulang jati diri. Membentuk karakter, sifat, watak, mental, dan kepribadian yang selaras dengan Pancasila. Menjadi manusia paripurna dalam berpikir, berbicara, bernarasi, dan berperilaku.
- Merawat warisan baik, mencipta kebaruan. Menjaga tradisi yang bernilai sambil menciptakan tradisi baru yang lebih baik. Nusantaraisme berpihak pada ilmu pengetahuan, mengharmoniskan iptek dan imtak.
- Industri dan iptek yang ramah alam. Mendorong hubungan harmonis antara Tuhan, manusia, dan alam (theo-antro-eco-centris) yang berlandaskan gotong royong tanpa ego.
- Menghapus mentalitas budak. Melepaskan diri dari mental pengemis, inlander, atau ambtenaar—budak bangsa yang memperbudak sesama. Nusantaraisme berporos pada kemerdekaan sejati: merdeka dari dan merdeka untuk.
- Berorientasi pada bumi surgawi. Mewujudkan bumi yang selaras, sejahtera, damai, adil, dan penuh kebahagiaan. Mengembalikan keseimbangan yang dirusak oleh manusia berwatak angkara, serakah, dan jahiliyah.
Pertanyaannya kini, di mana kita berpihak? Apakah kita akan berdiri di barisan nusantaraisme—setia pada tanah air dan sejarah—atau menjadi “Maling Kundang” zaman, yang khianat dan memuakkan?