KRISIS IDEOLOGIS DALAM EKOPOL PERDAGANGAN INDONESIA
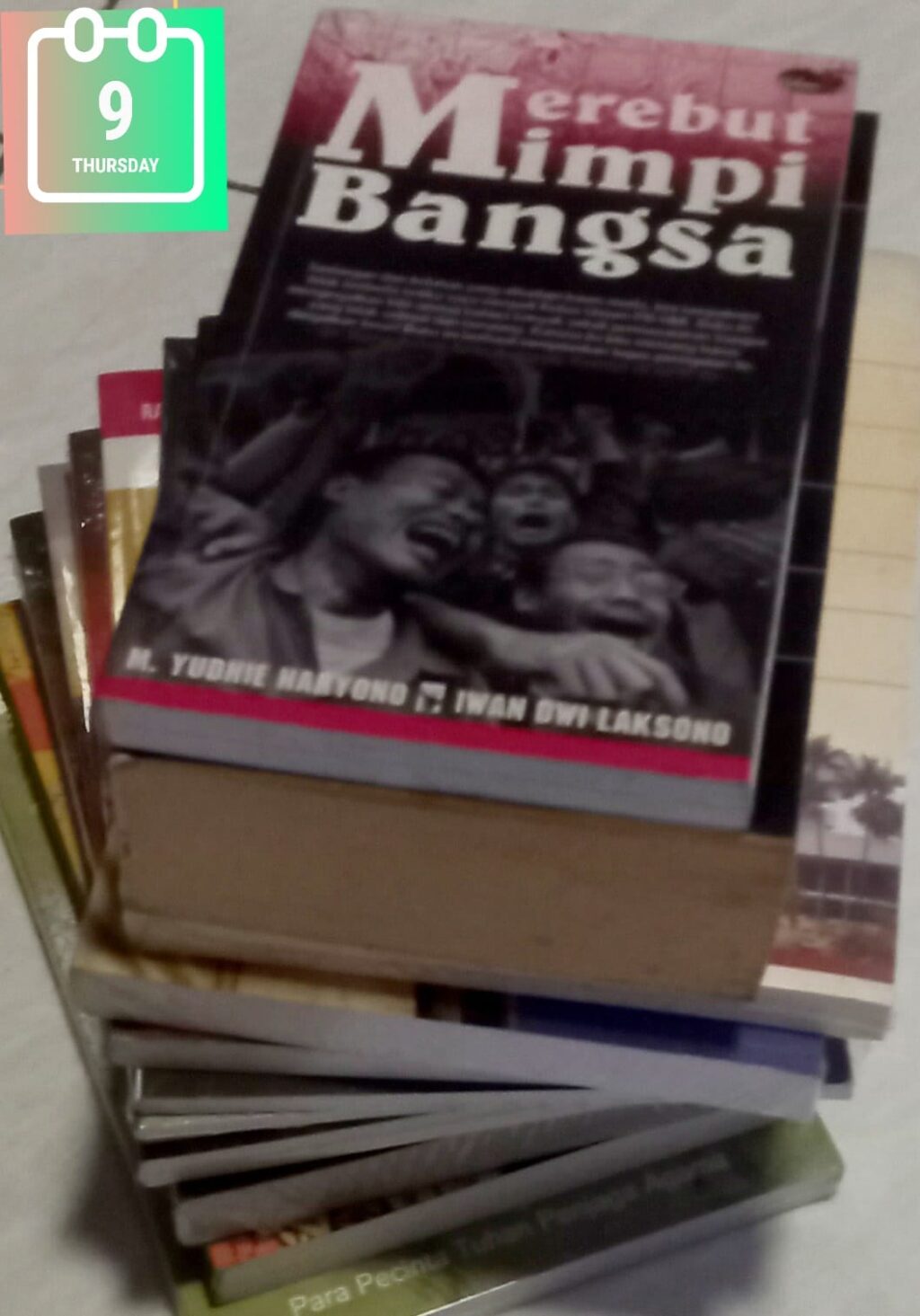
Oleh: Yudhie Haryono (Presidium Forum Negarawan), Agus Rizal (Ekonom Universitas MH Thamrin)
Otoritas.co.id – Peradaban rempah. Bangsa herbal. Komunitas jamu. Tetapi, pelan dan pasti sebutan-sebutan agung itu hilang dari republik. Generasi muda tidak mengenalnya, generasi tua melupakannya. Ya. Indonesia purba memang selalu bangga disebut sebagai tanah rempah. Namun di balik slogan itu tersembunyi kenyataan getir: negara ini kehilangan kendali atas perdagangan rempah dan herbal yang merupakan salah satu warisan strategisnya.
Sebagian besar aktivitas ekonomi di sektor ini justru berlangsung di luar sistem formal negara. Diremehkan. Dilupakan. Tidak tercatat, tidak dikenai pajak, dan tidak dikendalikan. Ini bukan sekadar masalah teknis pencatatan, melainkan cermin telanjang dari kerapuhan ideologis ekonomi nasional yang gagal membela kedaulatan sumber daya hayati.
Kajian lintas sumber daya alam yang diverifikasi menunjukkan bahwa 30 hingga 40 persen perdagangan rempah dan herbal Indonesia berlangsung tanpa tercatat di Kementerian Perdagangan atau BPS. Fakta ini didukung oleh laporan The Asia Foundation (2020), Outlook Komoditas Kementan (2022–2024), dan diskusi strategis BRIN (2023). Ratusan ribu ton produk seperti jahe, cengkeh, temulawak, hingga kayu manis, keluar dari sistem nasional melalui jalur informal yang tidak diawasi negara. Praktik ini sistemik, bukan insidental. Berlangsung tahunan, melibatkan banyak aktor tapi alpa “negara” dan tentu saja pemerintahan.
Secara ekonomi politik, ini berarti negara kehilangan dua hal sekaligus: fungsi regulator dan fungsi redistributor. Sebagai regulator, negara gagal mengontrol alur dan harga perdagangan. Sebagai redistributor, negara kehilangan potensi fiskal yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk membangun industri hilir, memberikan insentif petani, atau membiayai riset. Sebaliknya, yang untung adalah pedagang besar lintas batas, eksportir abu-abu, dan jaringan pembeli asing yang tidak pernah berurusan dengan negara.
Dalam perspektif ideologis, fenomena ini adalah bentuk nyata dari liberalisasi liar yang tidak dikendalikan negara. Prinsip ekonomi Pancasila, yang menekankan kedaulatan atas sumber daya strategis dan keadilan sosial, ditinggalkan demi praktik pasar bebas tanpa batas. Negara terlihat pasif bahkan abai, membiarkan warga negara bersaing bebas dalam struktur pasar yang timpang dan tidak transparan. Ini bukan pasar bebas yang sehat, tetapi pasar liar yang eksploitatif.
Persoalan ini juga memperlihatkan fragmentasi kelembagaan yang akut. Tidak ada satu otoritas tunggal yang bertanggung jawab atas tata kelola rempah dan herbal. Kementerian Pertanian fokus pada budidaya, Kementerian Perdagangan pada ekspor formal, Bea Cukai pada lalu lintas barang, sementara Kementerian Kesehatan dan BPOM hanya muncul saat bicara keamanan produk: obat dan jamu. Koordinasi antarsektor lemah, sehingga ruang gelap perdagangan terus terbuka.
Dalam kerangka ekonomi politik global, kondisi ini membuat Indonesia lemah dalam negosiasi internasional. Komoditas yang keluar secara tidak resmi tidak bisa digunakan sebagai basis diplomasi dagang. Tidak ada catatan asal-usul, tidak ada nilai tambah di dalam negeri, dan tidak ada klaim legal jika produk tersebut dipatenkan negara lain. Artinya, Indonesia bukan hanya dirugikan secara ekonomi, tetapi juga didepak dari arena geopolitik perdagangan hayati dunia.
Sebagian kalangan menyebut bahwa perdagangan informal ini merupakan bentuk “ekonomi rakyat”. Namun narasi itu menyesatkan. Dalam banyak kasus, petani dan produsen justru tetap mendapat harga rendah, sementara nilai ekspor penuh disedot oleh pihak ketiga yang tidak terikat pada regulasi nasional. Ketika negara tidak hadir dalam pengawasan, yang terbentuk bukan ekonomi rakyat, tetapi ekonomi tanpa negara, di mana hukum pasar menggantikan hukum konstitusi. Yang besar yang menang: oligarki mengangkangi.
Krisis ini harus dilihat sebagai kegagalan ideologi pembangunan. Selama tiga dekade terakhir, negara lebih sibuk membangun branding dan retorika geopolitik ketimbang membenahi struktur distribusi dan pengawasan komoditas. Tidak ada sistem traceability yang tegas, tidak ada ekosistem perizinan yang cepat, tidak ada insentif logistik yang mendorong produsen tetap di jalur legal. Negara ingin ekspor naik, tapi enggan membangun ekosistem yang mendukung.
Solusinya tentu bukan hanya soal perbaikan teknis birokrasi, tetapi harus dimulai dari pergeseran orientasi ideologi kebijakan: dari liberal-individualistik ke nasional-stratejik. Harus ada sistem nasional yang meletakkan rempah dan herbal sebagai komoditas strategis setara tambang dan migas, dengan pengawasan ketat dan perlindungan menyeluruh dari hulu ke hilir. Jika tidak, kebocoran 30–40 persen itu akan terus menjadi lubang hitam yang menyedot nilai tambah nasional ke luar negeri tanpa jejak.
Di era ketika dunia beralih ke produk natural, organik, dan herbal, Indonesia seharusnya tampil sebagai kekuatan sentral. Namun selama negara tidak menguasai rantai pasok, tidak menguasai data, tidak menguasai arus barang, dan tidak menguasai instrumen fiskal, maka Indonesia hanya akan menjadi penyedia bahan mentah tanpa nilai tawar.
Tentu ini bukan sekadar soal rempah, herbal dan jamu. Ini adalah soal kedaulatan ekonomi nasional dalam wujud paling konkret dan paling terancam. Mari segerakan panca dharma Indonesia agar merdeka kembali ekopol kita: (1)revolusi pemikiran; (2)revitalisasi kelembagaan; (3)rekonstruksi kurikulum pendidikan dan tradisi; (4)restrukturasi mental, (5)rekapitalisasi SDM dan SDA. Semoga mestakung.(*)






